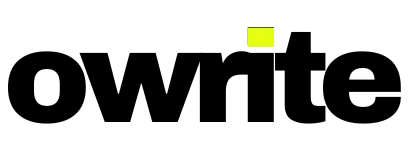Pernyataan Kementerian Sosial (Kemensos) mengenai skema jaminan hidup atau jadup sebesar Rp10.000 per hari per orang bagi korban banjir dan longsor di wilayah Sumatera bukan sekadar soal teknis bantuan sosial, melainkan cerminan negara memaknai keadilan sosial dalam situasi darurat.
Meski demikian, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang kerap disapa Gus Ipul, menyebut angka tersebut belum final karena masih merujuk pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) yang lama, yang ditetapkan pada tahun 2015. Revisi aturan pada 2020 ternyata juga tidak mengubah besaran bantuan jaminan hidup yang telah ditetapkan sebesar Rp10.000 per hari per orang. Namun, Gus Ipul mengusulkan bahwa dana bantuan tersebut besarannya dapat dinaikan menjadi Rp15.000.
Kemudian juga ada jaminan hidup yang selama ini (menggunakan) Permensos lama, Permensos lama ini yang kemudian, tolong jangan dipotong ya, Permensos lama itu sejak tahun 2015, ada revisi tahun 2020, nilainya tetap sama, besarnya tetap sama yaitu Rp10.000. Maka kami mengusulkan besarnya (Jaminan Hidup) ini dinaikkan dari Rp10.000 ke berapa nanti. Bantuan ini adalah per orang, per individu. Misalnya, ini misalnya jangan salah tulis lagi, misalnya nanti Rp15.000 per orang per hari. Untuk apa? Untuk membeli lauk-lauk,”
kata Gus Ipul kepada wartawan, Rabu, 24 Desember 2025.
Pernyataan Kementerian Sosial tentang jaminan hidup bukan sekadar soal skema bantuan, melainkan potret ‘telanjang’ bagaimana negara mengukur nilai minimum kehidupan warganya di saat paling rentan.
Mensos pun menyebut penyaluran bantuan akan berbasis data tunggal dari hasil pendataan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang digunakan bersama lintas kementerian agar bantuan tidak tumpang tindih.
Oh yang jaminan itu dalam bentuk tunai ya. Tunai Rp15.000,”
ujar Gus Ipul.
Secara administratif rapi. Secara moral, dipertanyakan. Sebab di tengah akses pasar yang terputus akibat bencana, Rp15.000 per hari apakah betul-betul merepresentasikan jaminan hidup atau sekadar penanda bahwa negara telah hadir, meski hanya sebatas tanda tangan anggaran.
Bencana, pada akhirnya, bukan hanya peristiwa alam. Ia adalah ujian bagi sistem perlindungan sosial: apakah dirancang untuk benar-benar melindungi, atau sekadar memastikan negara tetap terlihat bekerja di atas kertas. Jaminan hidup Rp10.000 memaksa publik bertanya ulang, bukan sekadar berapa besar bantuan yang pantas, tetapi seberapa serius negara menempatkan martabat korban sebagai pusat dari setiap kebijakan pemulihan.
Jadup Jadi Pelampung Cegah Kematian Instan
Menurut Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, dana jadup sebesar Rp10.000 sampai Rp15.000 per orang per hari bukan sekadar soal angka, melainkan soal cara negara memaknai hidup warganya dalam situasi krisis.
Ketika bencana alam, konflik sosial, atau kegagalan ekonomi memaksa warga kehilangan rumah, pekerjaan, dan penghasilan, negara hadir melalui skema jadup.
Namun yang perlu kita tanyakan secara jujur adalah apakah jaminan hidup (jadup) saat ini benar-benar menjamin hidup atau hanya menjaga agar warga tidak mati kelaparan secara statistik. Masalahnya bukan sekadar keterbatasan fiskal, melainkan desain kebijakan yang terjebak pada angka lama,”
kata Achmad pada Owrite, Rabu, 24 Desember 2025.
Dalam hemat Achmad, jadup masih diperlakukan sebagai bantuan simbolik, bukan sebagai instrumen perlindungan ekonomi yang nyata. Di sinilah letak persoalan mendasar yang perlu dirumuskan ulang.
Achmad kemudian menganalogikan seorang warga korban banjir besar yang kehilangan rumah dan warung kecilnya. Kemudian, negara datang memberi jaket pelampung tipis, cukup agar ia tidak langsung tenggelam, tetapi jauh dari cukup untuk membawanya ke daratan yang aman.
Jadup Rp10.000 per hari adalah jaket pelampung itu. Ia mencegah kematian instan, tetapi tidak memberi kesempatan hidup layak, apalagi pemulihan ekonomi. Analogi ini membantu kita memahami bahwa jadup bukan sekadar soal bertahan satu atau dua hari. Ia seharusnya menjadi jembatan menuju pemulihan, bukan sekadar alat penenang sosial agar krisis tidak terlihat terlalu parah,”
ungkap Achmad.
Secara ekonomi, menurut Achmad, relevansi Rp10.000 sampai Rp15.000 per hari hampir mustahil dipertahankan. Dengan harga beras rata-rata di atas Rp14.000 per kilogram, telur ayam Rp28.000 per kilogram, dan kebutuhan dasar lain seperti minyak goreng, sayur, air bersih, serta energi memasak, angka tersebut bahkan tidak cukup untuk satu kali makan bergizi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan garis kemiskinan nasional pada 2024 berada di kisaran Rp580.000 per kapita per bulan atau sekitar Rp19.000 per hari. Itu pun hanya untuk kebutuhan minimum, bukan kondisi darurat yang biasanya justru lebih mahal karena akses terbatas dan distribusi terganggu.
Jika jadup berada di bawah garis kemiskinan, maka secara logika ekonomi ia tidak mungkin disebut jaminan hidup. Ia hanyalah bantuan minimal untuk menunda kejatuhan yang lebih dalam. Di sinilah kegagalan konseptual terjadi, karena negara seolah mengakui standar hidup yang bahkan tidak mencapai batas kemiskinan resminya sendiri,”
bebernya.
Berapa Jadup yang Layak Disebut Jaminan Hidup?
Jika kita ingin jujur secara kebijakan publik, maka jadup minimum seharusnya berada di atas garis kemiskinan, bukan di bawahnya. Dengan mempertimbangkan inflasi pangan, biaya logistik darurat, dan kebutuhan non-pangan dasar seperti sabun, transportasi lokal, serta komunikasi, jadup ideal berada di kisaran Rp30.000 sampai Rp40.000 per orang per hari. Angka ini bukan kemewahan, melainkan refleksi realistis dari biaya hidup minimum dalam kondisi krisis,”
tegas Achmad.
Perhitungan ini sederhana, kata Achmad, tiga kali makan sederhana dengan gizi minimum membutuhkan setidaknya Rp25.000. Tambahan kebutuhan non-makanan harian membutuhkan sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000. Tanpa itu, korban bencana dipaksa mengorbankan kesehatan, pendidikan anak, atau bahkan menjual aset tersisa untuk bertahan.
Indonesia pun sebenarnya tidak kekurangan rujukan. Organisasi internasional seperti Bank Dunia dan UNHCR menggunakan pendekatan minimum expenditure basket dalam bantuan tunai darurat. Di banyak negara berkembang, bantuan tunai darurat ditetapkan setara 70 sampai 100 persen garis kemiskinan lokal.
Bahkan di negara tetangga seperti Filipina, bantuan darurat pascabencana disesuaikan secara berkala dengan inflasi pangan regional.
Artinya, standar internasional tidak pernah membekukan angka bantuan selama bertahun-tahun. Penyesuaian adalah keniscayaan. Ketika Indonesia mempertahankan angka jadup lama, kita bukan sedang berhemat, tetapi tertinggal secara tata kelola perlindungan sosial,”
jelasnya.
Kemudian, masalah berikutnya adalah kekaburan fungsi. Jadup seharusnya merupakan perlindungan sosial darurat, berbeda dari bansos reguler. Perlindungan darurat bersifat sementara tetapi intensif, bertujuan menjaga martabat hidup dan mempercepat pemulihan. Namun desain jadup saat ini lebih mirip perpanjangan bansos rutin, dengan nilai kecil dan pendekatan seragam.
Akibatnya, negara gagal membedakan antara kemiskinan struktural dan guncangan ekonomi mendadak. Korban kehilangan rumah dan usaha diperlakukan sama dengan penerima bantuan rutin, padahal kerugian ekonominya jauh lebih besar dan mendadak,”
katanya.
Desain jadup yang seragam juga mengabaikan fakta bahwa korban bencana tidak hanya kehilangan konsumsi hari ini, tetapi juga sumber penghidupan masa depan. Petani kehilangan lahan, pedagang kehilangan kios, buruh kehilangan pekerjaan.
Jadup yang hanya dihitung per kepala per hari tidak mempertimbangkan kehilangan pendapatan, aset, dan modal sosial. Di sinilah seharusnya negara masuk dengan pendekatan berbasis kerugian ekonomi riil. Jadup juga perlu dikaitkan dengan skema pemulihan usaha, padat karya darurat, atau bantuan modal awal.
Tanpa itu, jadup hanya menunda kemiskinan permanen, bukan mencegahnya,”
terangnya.
Adapun risiko terbesar dari mempertahankan jadup lama bukan hanya penurunan kesejahteraan korban, tetapi juga erosi kepercayaan publik. Ketika warga merasa negara hadir dengan angka yang tidak masuk akal secara ekonomi, legitimasi kebijakan sosial melemah.
Selain itu, jadup yang terlalu kecil mendorong strategi bertahan hidup negatif, seperti utang berbunga tinggi, eksploitasi anak, atau migrasi paksa. Dalam jangka panjang, biaya sosial dari kebijakan yang tidak realistis justru lebih mahal dibandingkan penyesuaian jadup itu sendiri.
Negara menghemat hari ini, tetapi membayar lebih mahal di masa depan melalui kemiskinan kronis dan ketimpangan yang memburuk,”
bebernya.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang Rp10.000 per hari adalah pertanyaan tentang keberanian politik dan kejujuran kebijakan. Jika negara ingin menyebutnya jaminan hidup, maka ia harus berani menyesuaikan angka dengan realitas ekonomi. Jika tidak, lebih jujur menyebutnya bantuan simbolik darurat.
Jadup harus dipahami sebagai instrumen perlindungan sosial yang hidup, adaptif, dan manusiawi. Menyesuaikan nilainya bukan pemborosan, melainkan investasi sosial agar warga tidak terperosok lebih dalam saat krisis datang.
Dalam konteks itulah, menaikkan jadup bukan soal belas kasihan, tetapi soal rasionalitas ekonomi dan tanggung jawab negara terhadap martabat hidup warganya,”
tekan Achmad.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, menegaskan bahwa hingga saat ini Kementerian Sosial belum mengajukan anggaran tambahan 2026 untuk jadup.
Info dari DJA, Kementerian Sosial belum mengajukan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan. Untuk teknisnya silahkan tanyakan langsung ke Kementerian Sosial ya,”
jelas Deni.
Perdebatan soal jaminan hidup pascabencana di Sumatera bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Di berbagai belahan dunia, skema bantuan tunai pascabencana telah lama menjadi instrumen kebijakan dengan besaran, desain, dan hasil yang sangat beragam.
Pertanyaan menjadi semakin tajam ketika Presiden memilih menutup pintu bantuan internasional. Jika negara memutuskan berdiri sendiri dalam menghadapi bencana, maka seluruh perhatian publik wajar diarahkan pada satu hal: seberapa kuat, seberapa adil, dan seberapa manusiawi negara menopang warganya yang terdampak.
Pakistan
Menghadapi banjir mematikan pada 2010, Bank Dunia (World Bank) menyetujui kredit sebesar US$125 juta atau setara dengan Rp2,095 triliun (estimasi kurs: Rp16.760) untuk Proyek Transfer Tunai Darurat Banjir, yang dirancang untuk mendukung Program Kompensasi Kerusakan Warga (CDCP) Pemerintah Pakistan dalam memberikan transfer tunai kepada lebih dari 1 juta rumah tangga yang terkena dampak banjir.
Melansir dari situs resmi Bank Dunia, proyek ini juga akan memperkuat manajemen CDCP melalui mekanisme penyelesaian pengaduan yang efektif dan menetapkan langkah-langkah pengendalian dan akuntabilitas untuk memastikan penyampaian dukungan yang efisien dan transparan.
Diluncurkan pada September 2010, CDCP memberikan bantuan tunai sebesar sekitar US$230 (Rp3,8 juta) kepada sekitar 1,4 juta keluarga untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Fase selanjutnya, yang didukung oleh proyek ini, akan memberikan pembayaran tambahan sebesar sekitar US$460 (Rp7,7 juta) kepada sekitar 1,1 juta rumah tangga yang paling terdampak, sehingga menjangkau antara 7,5 dan 8,3 juta orang untuk membangun kembali kehidupan mereka. Untuk memenuhi total kebutuhan pembiayaan CDCP, Bank Dunia telah bekerja sama erat dengan mitra pembangunan lainnya, beberapa di antaranya (USAID dan Italia) telah berkomitmen memberikan dana.
Amerika Serikat
Federal Emergency Management Agency (FEMA) juga menyediakan bantuan uang tunai langsung kepada individu dan keluarga yang terkena bencana, misalnya untuk tempat tinggal sementara, kebutuhan dasar, dan biaya pemulihan, selain bantuan lain seperti rumah darurat dan dukungan medis. Program ini bisa mencapai ratusan hingga ribuan dolar tergantung kebutuhan dan kerusakan rumah korban.
FEMA pun menghabiskan total anggaran bersih sebesar US$35,1 miliar (Rp588,3 triliun) pada tahun 2024. Jumlah ini merupakan 39,3 persen dari US$89,3 miliar (Rp1,4 kuadriliun) yang dihabiskan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), yang merupakan 1,3 persen dari total pengeluaran federal. FEMA juga menempati peringkat pertama di antara subdivisi DHS dalam hal pengeluaran bersih.
Dominika
Beberapa negara Karibia setelah badai besar menyediakan cash grants (hibah tunai) kepada keluarga yang kehilangan rumah, misalnya bantuan tunai sekitar US$334 (RP5,5 juta) per keluarga disalurkan melalui kartu debit untuk kebutuhan pemulihan jangka pendek setelah Badai Tropis Erika di kawasan tersebut.
Skotlandia
Meski ini bukan program langsung pemerintah nasional Malawi sendiri, pemerintah Skotlandia bersama lembaga GiveDirectly memimpin program cash transfer untuk korban bencana Topan Freddy di Malawi pada 2024 lalu, dengan memberikan sekitar US$750 (Rp12,5 juta) per rumah tangga selama beberapa bulan untuk membantu pembangunan rumah di tempat baru setelah bencana, tanpa adanya persyaratan apapun. Ini disebut sebagai salah satu cash transfer pertama di dunia untuk “loss and damage” akibat perubahan iklim.
Menurut penilaian kebutuhan pascabencana pemerintah, Topan Freddy menewaskan 679 orang dan menyebabkan 659.000 orang mengungsi di Malawi selatan. Badai tersebut menyebabkan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi senilai US$506,7 juta (Rp8,4 triliun).
Pada akhirnya, perdebatan tentang jaminan hidup bukanlah perdebatan tentang rupiah semata. Ia adalah perdebatan tentang bagaimana negara mendefinisikan kewajiban moral ketika warganya kehilangan segalanya.
Di tengah reruntuhan rumah, sawah yang rusak, dan penghidupan yang terhenti, bantuan negara bukan sekadar instrumen kebijakan, melainkan satu-satunya jangkar yang menahan korban agar tidak terjatuh lebih jauh ke jurang kemiskinan dan keputusasaan.
Ketika negara memilih untuk berdiri sendiri tanpa bantuan internasional, pilihan itu secara otomatis menaikkan standar tanggung jawab domestik. Kemandirian, dalam konteks ini, bukan slogan, melainkan komitmen yang harus tercermin dalam kualitas dan kecukupan perlindungan sosial. Jika yang ditawarkan hanya angka minimal yang nyaris tak mampu menjamin kebutuhan paling dasar, maka klaim kemandirian berubah menjadi beban yang dipikul oleh mereka yang paling rentan.
Jaminan hidup seharusnya menjadi jembatan menuju pemulihan, bukan sekadar penanda administratif bahwa negara telah hadir. Ia seharusnya memberi ruang bernapas, waktu untuk bangkit, dan rasa aman sementara bagi keluarga yang hidupnya terputus oleh bencana. Tanpa itu, bantuan hanya akan berfungsi sebagai penunda kejatuhan, bukan alat pemulihan.