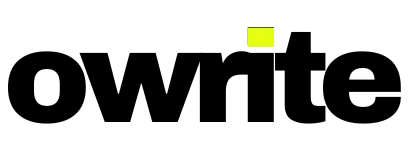Ruang Credential, Istana Merdeka, 2 Oktober 2014 malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku telah menandatangani dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) perihal ketidaksetujuannya atas keputusan parlemen yang menetapkan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dilakukan melalui DPRD.
Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota; dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah resmi ia teken dan diundangkan pada hari yang sama.
Kedua Perppu tersebut saya tandatangani sebagai bentuk nyata dari perjuangan saya bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung,”
kata SBY.
Ia mendukung penuh Pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar. Meskipun menghormati proses pengambilan keputusan terkait RUU Pilkada di DPR, yang memutuskan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD, Presiden SBY tetap berikhtiar demi tegaknya kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Presiden mengerti dan memaklumi kekecewaan, bahkan kemarahan sebagian besar rakyat Indonesia yang merasa hak dasarnya untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin di daerahnya masing-masing dicabut dengan Pilkada tidak langsung melalui DPRD.
Kekecewaan demikian menurut saya adalah wajar, saya sendiripun juga merasakan kekecewaan yang sama,”
aku dia.
(Tolak) Jilat Ludah Sendiri
Perubahan sikap ini menjadi sorotan, mengingat Partai Demokrat di bawah era SBY pernah dikenal sebagai “penjaga gawang” Pilkada Langsung lewat penerbitan dua Perppu tersebut.
Menanggapi polemik ini, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf, menegaskan bahwa langkah partainya bukan bentuk ketidakkonsistenan, melainkan respons terhadap dinamika politik dan evaluasi objektif atas pelaksanaan demokrasi satu dekade terakhir.
Tidak bisa dibilang berbalik pikiran, tetapi politik itu dinamis, tiap periode punya masanya. 10 tahun (terakhir) ini (Indonesia) sudah melaksanakan Pilkada terbuka. Pada kenyataannya, ini juga berdasarkan data yang ada, bahwa tidak berarti kepala daerah hasil pilihan terbuka ternyata mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan baik,”
kata dia di gedung DPR, 8 Januari 2026.
Justru, lanjut Dede, sistem langsung memicu efek samping yang masif: biaya politik tinggi yang berujung pada korupsi. Sehingga kepala daerah kerap berurusan dengan penegak hukum dan ia berdalih “penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan secara demokratis.”
Perihal keraguan soal konstitusionalitas, Dede berargumen bahwa definisi “demokratis” dalam Undang-Undang Dasar tidak melulu bermakna one man one vote. Pemilihan melalui perwakilan di parlemen daerah juga merupakan bentuk demokrasi yang sah secara hukum.
Demokratis itu bisa terbuka secara langsung, bisa juga tertutup. Tertutup artinya apa? Dipilih oleh DPRD karena itu bagian dari perwakilan. Oleh karena itu tidak melanggar undang-undang dan kami bisa mencoba dengan tujuan efisiensi penghematan alokasi anggaran,”
kata dia, merujuk pada besarnya biaya penyelenggaraan pemilu dan sengketa hasil (PSU) yang terjadi pada 2024 akibat maraknya politik uang.
Dede menekankan, Demokrat tidak ingin hak publik diamputasi sepenuhnya. Ia mengusulkan, mekanisme hibrida yakni calon kepala daerah tetap harus diuji publik sebelum dipilih oleh anggota dewan. Konsep uji publik tersebut bisa berupa pemaparan visi-misi terbuka atau dialog warga.
Apakah dalam pemaparan visi-misi kampanye atau mungkin juga kita menyebutnya town hall meeting. Bahwa nanti kemudian dipilih oleh DPRD setelah calon ini memperkenalkan dirinya juga keluar kepada publik,”
jelas dia.
Poin paling krusial dari pernyataan Dede ialah penegasan posisi politik Demokrat saat ini. Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, Demokrat menyatakan bakal loyal terhadap arah kebijakan yang diambil oleh kepala negara.
Jadi sekali lagi, pada prinsipnya Demokrat ikut pada pilihan presiden. Karena presiden yang akan menjaga dan mengawal demokrasi agar berjalan sebaik-baiknya,”
ujarnya.
Pragmatisme Anak Kandung di Simpang Jalan
Demokrat adalah “kiper” demokrasi langsung lewat penerbitan Perppu Pilkada di bawah tangan SBY. Kini, di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), anak kandung SBY, arah angin partainya hampir berubah 180 derajat.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo, berpendapat manuver Demokrat bukan sekadar perubahan haluan biasa, melainkan taktik “cari selamat” di tengah arus deras koalisi penguasa. Demokrat dinilai sedang memainkan kartu pragmatisme demi mengamankan posisi dalam kabinet Prabowo dan menghindari isolasi politik.
Menurut Kunto, Demokrat menyadari adanya risiko kerusakan citra (brand damage) akibat inkonsistensi ini. Namun, kalkulasi politik mereka bertumpu pada satu asumsi: ingatan pemilih Indonesia yang pendek.
Kerusakan pasti ada, tapi masalahnya pemilih itu pelupa. Demokrat mungkin berpikir ‘pemilu masih lama, masih 3-4 tahun lagi’. Kalaupun mendukung Pilkada melalui DPRD, itu mungkin akan mudah dilupakan oleh pemilih,”
ucap Kunto kepada owrite.
Lupa menjadi lubang bagi politik negeri. Seperti perdebatan lebih dahulu ayam atau telur: tidak rampung. Salah satu tanggung jawab partai ialah memberikan pendidikan politik, namun itu tidak dilakukan dengan optimal. Akhirnya, partai memilih politik uang untuk memuluskan niat.
Kini, Demokrat belajar dari pengalaman pahit Pemilu 2024. Saat itu, Demokrat mengambil posisi kontras sebagai oposisi yang menolak kenaikan BBM, namun hal tersebut tidak berbuah manis secara elektoral. Sehingga Demokrat pun bisa saja berpikir, “ngapain harus melakukan sesuatu yang secara politik praktis berisiko?”
Strategi yang diambil saat ini adalah blending in atau membaur. Ketika partai-partai besar di koalisi pemerintah mendukung Pilkada via DPRD, Demokrat memilih untuk tidak menjadi duri dalam daging. Keuntungan ini tak hanya berlaku bagi AHY cs, partai lain pun bisa mengikuti jejaknya demi tak menjadi batu sandungan.
Secara politik riil, koalisi partai yang berkuasa maunya dukung Pilkada via DPRD. Kalau Demokrat tidak mendukung, itu melemahkan posisi mereka. Jadi lebih baik diambil yang menguntungkan sekarang, jangan kehilangan keuntungan secara politik, tapi juga risiko paling kecil,”
tambah Kunto.
Terkait alasan “biaya politik mahal” dan “politik uang” yang didengungkan Dede Yusuf, Kunto melihatnya sebagai narasi tunggal yang seragam dengan pemerintah. Meski argumen ini sulit diterima oleh nalar kritis kaum muda (Gen Z dan Milenial), situasi ekonomi membuat rakyat menjadi apatis terhadap mekanisme demokrasi.
Masyarakat tengah terjepit masalah ekonomi riil seperti lapangan kerja dan harga bahan pokok, sehingga tidak memiliki energi lebih untuk memprotes cara pemilihan kepala daerah. Imbasnya, publik hanya merasa “siapapun kepala daerah terpilih, asal gampang cari kerja.”
Fenomena ini diperparah dengan rendahnya literasi politik. Kunto mencontohkan kasus Undang-Undang Ibu Kota Negara. Sebelum disahkan, mayoritas publik menolak. Namun, setelah regulasi itu disahkan lewat proses kebut semalam parlemen, opini publik berbalik mendukung lantaran menganggap produk undang-undang adalah kebenaran mutlak dan tak perlu dibantah.
Opini publik (Indonesia) masih sangat dipengaruhi oleh birokrasi formal. Kalau ada undang-undangnya, orang merasa itu benar. Ketika Pilkada oleh DPRD disahkan, sangat mungkin opini publiknya juga berbalik setuju,”
papar dia.
Sorotan tajam juga diarahkan pada posisi Ketua Umum Demokrat, AHY. Langkah ini berisiko menggerus legitimasi AHY sebagai penerus ideologis SBY. Publik mengenang SBY sebagai tokoh yang menjamin kebebasan sipil dan demokrasi langsung, ketika ia menduduki kursi orang nomor wahid di negeri ini.
Kalau anak kandung, anak darah, ya memang iya (AHY anak SBY), tak bisa dipungkiri. Tapi anak ideologis jadi beda. Ketika AHY berpindah haluan, orang akan sulit membayangkan AHY sebagai anak ideologisnya SBY,”
ujar Kunto.
Anggap saja saat ini Demokrat “membelot” dari DNA SBY. Bila ada skenario, misalnya pada Pemilu 2029 AHY menang—entah menjadi presiden atau wakil presiden— lantas ia kembali “memberontak” dengan pilihannya, maka itu tergantung dari kemampuan AHY dan elite-elite Demokrat hari ini untuk menanamkan persepsi anyar ihwal Demokrat.
Ketika AHY merevisi dengan tindakan-tindakannya sekarang atau pilihan-pilihan politik sekarang, bahkan mungkin nanti kalau terpilih jadi wakil presiden maupun presiden, maka AHY harus punya strategi untuk perang persepsi dengan dengan legasi bapaknya,”
jelas Kunto.
Itu PR yang sangat berat, menurut saya. Bahkan sebelum pemilihan, seharusnya sudah selesai. Jadi, identitas baru Demokrat yang ditawarkan yang seperti apa, gitu. Itu yang mungkin ditunggu oleh loyalis dan simpatisan Demokrat atau orang-orang (yang melihat) figur SBY,”
sambung dia.
Fenomena putar balik Demokrat ini semakin menegaskan, bahwa Indonesia telah terperangkap dalam sistem oligarki: partai politik tidak lagi menjadi penyambung lidah rakyat, melainkan perpanjangan tangan elite dan bohir.
Sistem prinsip oligarki memang government by the few (pemerintahan oleh segelintir orang). Apa yang dilakukan Demokrat hari ini justru semakin memperkuat tesis itu, bahwa Indonesia memang oligarki, bukan demokrasi,”
jelas Kunto.
Kondisi ini menyisakan ironi: Pemilih di Indonesia pada akhirnya tidak lagi melihat visi-misi atau ideologi partai karena semuanya seragam, melainkan hanya bergantung pada ketokohan. Problem muncul ketika sang tokoh idola (SBY), memiliki rekam jejak yang bertolak belakang dengan keputusan partai saat ini.