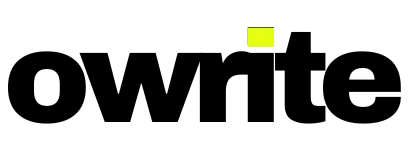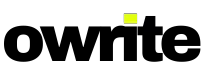Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar, menilai fenomena “Mens Rea” Pandji bukan sekadar sengketa antara komedian dan kelompok masyarakat, melainkan sinyal bahaya bagi kebebasan sipil dan tata kelola pemerintahan (good governance).
Salah satu poin krusial dalam materi Pandji adalah kritik terhadap pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada ormas keagamaan. Namun, kritik kebijakan publik ini justru dibalas dengan laporan pencemaran nama baik organisasi.
Adinda melihat ini sebagai bukti rentannya pasal-pasal dalam legislasi Indonesia, termasuk KUHP baru, yang sarat interpretasi ganda. Hukum telah dijadikan alat pembungkam partisipasi publik.
Ini menunjukkan betapa rentannya multiinterpretasi terhadap pasal-pasal legislasi. Sehingga hukum menjadi justifikasi untuk mengkriminalisasi suara-suara kritis terhadap pihak terkait proses kebijakan, termasuk dalam hal ini adalah atas nama organisasi,”
ucap Adinda kepada owrite.
Pola ini memenuhi unsur Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Kritik terhadap tata kelola tambang—yang sejatinya adalah isu publik—dianggap sebagai serangan personal atau organisasi. Dampaknya sangat serius: ketakutan psikologis masyarakat untuk bersuara.
Ini menjadi alat yang dianggap legal untuk membatasi partisipasi publik. Orang secara psikologis akan takut bersuara, karena ada kemungkinan dipidanakan.
Jika kritik kebijakan dianggap tabu dan kriminal, Adinda memperingatkan akan terciptanya echo chamber (ruang gema) dalam pemerintahan. Padahal kritik harus dibedakan dengan pencemaran nama baik.
Demokrasi akan dijustifikasi oleh proses kebijakan yang tidak didasarkan asas umum pemerintahan yang baik. Suara yang muncul hanya dari pendukung pihak berkuasa saja, karena yang lain takut. Bayangkan, tidak semua orang punya sumber daya untuk menjalani proses hukum kalau dia tidak punya kenalan atau ‘orang dalam’,”
tambah dia.
Selain isu tambang, Pandji juga disorot FPI terkait materi yang dianggap menyinggung perilaku salat namun tetap korupsi. FPI menuntut konten dihapus dari Netflix.
Adinda menilai, masuknya tekanan massa (mob justice) menggeser isu tata kelola menjadi politik identitas.
Ini menjadi pemicu untuk mengangkat isu lain yaitu politik identitas. Jika konten harus dihapus karena tekanan massa, ini jelas melanggar konstitusi dan kovenan kebebasan sipil yang sudah ditandatangani Indonesia,”
jelas Adinda.
Negara harus hadir dan tidak boleh kalah oleh tekanan kelompok mayoritas atau pressure group manapun. Hukum, tata kelola, dan demokrasi haram didikte oleh kemarahan massa.
Seharusnya hukum dan demokrasi kita tidak ditekan oleh tekanan mayoritas. Buat saya terlalu dangkal dan manipulatif jika memanfaatkan isu ini untuk memunculkan politik identitas,”
kata Adinda.
Adinda mempertanyakan kompetensi penyelenggara negara jika mudah goyah oleh tekanan semacam ini.
Kalau itu urusannya adalah nyali, publik jadi tahu kompetensi policy makers seperti apa. Apa mudah dialihkan oleh tekanan kelompok masyarakat tertentu untuk sesuatu yang menurut saya tidak krusial?”
ujarnya.
Publik pun harus paham—dan teredukasi—bahwa ini bukan isu agama sama sekali, melainkan isu pemerintahan dan demokrasi yang bukan saja mengkritisi pembuat kebijakan, tapi juga masyarakat sipil.
Ini sebenarnya adalah bagian yang sah saja dari kebebasan sipil. Maka negara wajib hadir guna mematikan kebebasan sipil dilindungi,”
tambah dia.
Kalau banyak orang mudah tersinggung, bisa saja penjara itu bisa makin penuh dan hal tersebut sama sekali tidak memberi ruang bagi publik untuk mengkritisi hal yang semestinya diperbaiki.
Perihal materi “salat tapi korupsi”, Adinda menilai itu adalah kritik sosial yang valid secara statistik dan realitas politik di Indonesia, yakni simbol agama kerap dijadikan komoditas politik namun pelakunya tetap korup.
Sayangnya, publik dan kelompok tertentu gagal meresponsnya dengan narasi tandingan yang cerdas. Masyarakat Indonesia belum matang seutuhnya.
Kritik sosial ini gagal menjadi diskusi publik yang sehat lantaran tak bertemu lawan sepadan. Semestinya ada pertarungan ide, bukan litigasi hukum.
Adinda membandingkan dengan fenomena novel The Da Vinci Code karya Dan Brown yang sempat memicu kontroversi global. Saat itu, respons yang muncul ialah lahirnya buku-buku tandingan dan debat teologis, bukan sekadar pelarangan atau pemenjaraan.
Kenapa mereka (kelompok yang tersinggung) tidak membuat konferensi pers atau stand-up tandingan untuk membalas argumen Pandji? Anggap saja ini pertempuran ide, sehingga masyarakat teredukasi,”
saran Adinda.
Menanggapi pernyataan Habiburokhman yang menjamin Pandji “aman dari penjara”, Adinda justru melihatnya sebagai ironi. Dalam negara hukum, rasa aman warga negara seharusnya dijamin oleh sistem yang baku, bukan oleh janji lisan politisi atau “orang dalam”.
Saya tidak percaya bahwa keamanan atau wellbeing seseorang itu dijamin oleh satu orang tertentu,”
tegas Adinda.
Hukum tetap menjadi panglima, bukan jaminan dari Habiburokhman. Jaminan lisan semacam ini justru mengonfirmasi persepsi publik bahwa hukum di Indonesia tebang pilih dan bergantung pada kedekatan dengan kekuasaan.
Hal ini berbahaya bagi mereka yang tidak populer atau tidak memiliki akses politik, seperti kasus aktivis yang masih mendekam di penjara.
Last but not least, ini menjadi ujian juga terhadap demokrasi dan penegakan hukum, bukan ditentukan oleh DPR atau individu manapun. Keberpihakan harus pada hukum, keadilan, dan kebenaran. saya tegaskan, ini seharusnya bukan hanya kasus Pandji,”
tutur Adinda.
Lelucon Penguji Akal Sehat
Asfinawati, Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, membedah fenomena Pandji bukan sekadar kasus hukum biasa, melainkan cermin retaknya sistem demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Kasus Pandji adalah judicial harassment (pelecehan yudisial) yang dipelihara negara.
Pandji dilaporkan oleh kelompok yang mengatasnamakan pemuda Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ihwal materi kritik tambang.
Padahal, PBNU dan PP Muhammadiyah secara resmi membantah memberikan mandat pelaporan tersebut.
Asfinawati berpendapat meski delik yang digunakan mungkin bukan delik aduan murni (tergantung pasal yang dipakai), laporan ini sejatinya sudah cacat iktikad baik.
Publik harus membedakan laporan beritikad baik dengan laporan yang mengada-ngada. Tahu dari mana? Ya, isi laporan. Yang dilakukan Panji merupakan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat dan sebetulnya bagian dari demokrasi karena karena isu-isu yang diangkat dalam acara itu adalah isu yang sangat bermanfaat untuk menjaga demokrasi,”
kata Asfinawati kepada owrite.
Karena patut diduga pelaporan itu tidak punya iktikad baik. Karena itu, menurut saya, laporannya pun tidak bermutu, dan bukan berasal dari organisasi. Sepatutnya secara politik penegakan hukum, laporan harus diabaikan, tidak perlu dilanjutkan karena ini mengada-ngada,”
sambung dia.
Ia menilai bila polisi bertindak profesional dan memiliki kepekaan politik hukum, laporan semacam ini seharusnya diabaikan sejak awal.
Aapalagi polisi dibayar pakai uang pajak negara. Kemampuan polisi menindaklanjuti laporan warga tergolong rendah sekali.
Kalau perkara Pandji diladeni, artinya menghabiskan kemampuan polisi untuk hal yang tidak menimbulkan kerugian nyata.
Penggunaan atribut ormas untuk mempolisikan kritik sebagai bentuk judicial harassment atau pelecehan melalui mekanisme hukum. Ini mengingatkan pada pola represi lama di Indonesia ketika ormas kerap digunakan sebagai alat pukul kekuasaan.
Penggunaan ormas ini sebetulnya pengulangan model baru. Sekarang dalam Undang-Undang Ormas ada larangan bagi ormas untuk menggeruduk, untuk berperilaku seperti polisi. Maka mereka menguba caranya dengan pelaporan,”
jelas Asfinawati.
Lantas, perihal FPI yang menuduh Pandji menista agama karena menyindir perilaku “salat tapi korupsi” juga disorot tajam.
Asfinawati menegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, delik penodaan agama seperti yang dipahami FPI sebenarnya tidak ada lagi landasan hukumnya.
Sederhananya, KUHP baru dan UU Penyesuaian Pidana itu menghapus Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.
Jadi delik penodaan agama sudah tidak ada,”
kata Asfinawati.
Dalam aturan baru (UU Penyesuaian Pidana) objek delik bukan lagi “agama” itu sendiri, melainkan serangan terhadap “orang/kelompok” berdasarkan agama dengan tujuan menghasut kekerasan atau permusuhan.
Secara substansi, Asfinawati juga membela materi Pandji. Kritik terhadap perilaku koruptif umat beragama bukanlah serangan terhadap ajaran agama, melainkan upaya meluruskan praktik yang salah.
Dia bukan mengkritik agama, tapi dia mengkritik praktik buruk. Sebetulnya justru akan melindungi agama, kan? Masa agama mengajarkan korupsi?”
jelas Asfinawati.