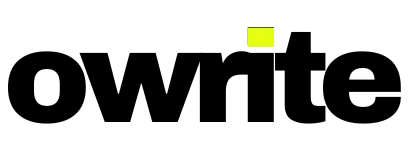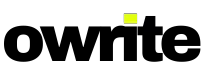Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat masih berdiri megah, namun jiwa penghuninya kian terasa samar.
Tahun 2025 digadang-gadang sebagai tahun “pemulihan luka” usai guncangan hebat Putusan Nomor 90 Tahun 2023 yang memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai orang nomor dua di Indonesia —dan kemudian Anwar Usman dicopot dari kursi Ketua Mahkamah Konstitusi.
Publik berharap di tahun pertama pemerintahan baru ini, MK kembali tegak sebagai Penjaga Konstitusi (The Guardian of Constitution).
Namun, rekam jejak putusan sepanjang 2025 justru menceritakan kisah sebaliknya: sebuah kegamangan lembaga peradilan, bahkan cenderung kompromis saat berhadapan dengan kepentingan kekuasaan yang semakin terkonsolidasi.
1. Melegitimasi Kabinet Gemuk
Ujian independensi paling nyata di tahun 2025 datang dari uji materi (Judicial Review) terhadap revisi Undang-Undang Kementerian Negara.
Koalisi masyarakat sipil menggugat penghapusan batasan jumlah kementerian, karena dinilai melanggar prinsip efisiensi anggaran negara dan membuka pintu bagi politik transaksional sebagai beban APBN.
Namun, realita putusan ialah Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut. Para hakim konstitusi kembali berlindung di balik tameng sakti bernama “Open Legal Policy” (Kebijakan Hukum Terbuka).
Hakim berdalih bahwa jumlah kementerian adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden. Dampaknya, putusan ini sebagai “stempel basah” pelegalan kabinet super gemuk (40+ menteri dan 49 kementerian) pemerintahan Prabowo-Gibran.
Publik menilai, mahkamah gagal berfungsi sebagai rem bagi ambisi eksekutif, malah justru menjadi pelicin jalan bagi akomodasi politik pemboros anggaran.
2. Sengketa Pilkada
Tahun 2025 disibukkan dengan penyelesaian ratusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah serentak 2024. Janji untuk memeriksa keadilan substantif (kecurangan terstruktur, sistematis, dan sasif) ternyata jauh panggang dari api.
Dalam sengketa-sengketa krusial di wilayah strategis seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara (Sumut), yakni ketika para calon yang berafiliasi dengan kekuasaan pusat menang, hakim mahkamah cenderung menolak gugatan pemohon.
MK kembali terjebak pada paradigma lama sebagai “Mahkamah Kalkulator”. Fokus persidangan hanya berkutat pada selisih angka perolehan suara.
Akibatnya, dalil perihal politisasi bantuan sosial daerah, ketidaknetralan ASN, dan mobilisasi aparat desa yang diajukan pemohon, rata-rata dikesampingkan lantaran dianggap “tidak cukup bukti”.
Mahkamah gagal membuktikan keberanian memutus mata rantai dinasti politik di daerah.
3. Presidential Threshold
Masyarakat sipil tak henti mencoba mendobrak ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) 20 persen agar pemilu 2029 lebih demokratis.
Tahun 2025, gugatan ini kembali mendarat di meja hakim konstitusi. Hasilnya, lagi-lagi gugatan ditolak. Konsistensi MK dalam mempertahankan ambang batas 20 persen menunjukkan stagnasi pemikiran hukum.
Saat publik berteriak bahwa regulasi ini membatasi pilihan rakyat dan melanggengkan kekuasaan oligarki partai, MK justru menutup mata dan telinga.
Tidak ada terobosan progresif di tahun 2025 untuk memperbaiki kualitas demokrasi elektoral masa depan.
4. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Salah satu upaya pemulihan citra adalah dengan mempermanenkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Namun, keberadaannya tahun ini terasa seperti “macan ompong”.
Sepanjang tahun, masuk beberapa laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, seperti pernyataan publik hakim yang bias hingga dugaan pertemuan dengan pihak berperkara.
Faktanya, sanksi yang keluar mayoritas hanya berupa “teguran lisan” atau “teguran tertulis ringan”. Dampaknya, publik menilai MKMK bukan sebagai pengadil etik yang garang, melainkan sebagai “kanal pelepasan” emosi publik semata.
Tidak ada sanksi tegas yang mampu memberikan efek jera, sehingga budaya permisif terhadap pelanggaran etik kecil tetap lestari di kalangan hakim.
5. Putusan minor
Agar tak terlihat sepenuhnya berpihak pada penguasa, MK memberikan beberapa kemenangan kecil bagi masyarakat sipil, namun pada isu yang tidak mengganggu struktur kekuasaan.
Contoh, MK mengabulkan sebagian uji materi ihwal regulasi ketenagakerjaan teknis atau isu lingkungan hidup skala mikro.
Kemenangan-kemenangan ini penting, namun bersifat parsial. Pengamat hukum menilai ini sebagai strategi “politik penyeimbang” dari MK, yaitu memberi hati pada kasus rakyat kecil, tapi tetap setia mengamankan kepentingan politik elite pada kasus-kasus ketatanegaraan yang strategis, seperti Undang-Undang Kementerian dan Threshold.