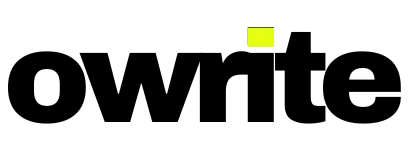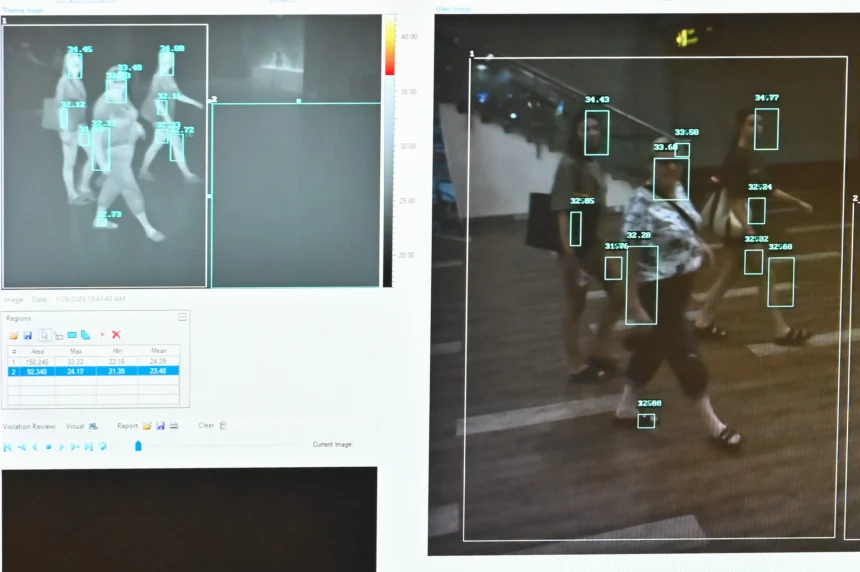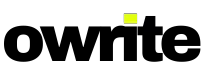Tahun 1828, pemerintah Kerajaan Belanda memberikan octrooi atau hak-hak istimewa kepada De Javasche Bank (DJB) untuk bertindak sebagai bank sirkulasi pertama di Asia.
Sebagai bank sirkulasi, lembaga itu berwenang mencetak dan mengedarkan uang Gulden di wilayah Hindia Belanda.
Octrooi secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Secara keseluruhan, DJB telah melalukan tujuh kali masa perpanjangan octrooi.
Tahun 1922, pemerintah Belanda menerbitkan Undang-Undang De Javasche Bank Wet. Pemerintah kolonial pun menggunakan DJB untuk mendukung kebijakan finansial dari sistem tanam paksa.
Rentang 1829-1870, DJB melakukan ekspansi bisnis dengan membuka kantor cabang di beberapa kota di Hindia Belanda, termasuk di luar Jawa: Semarang (1829), Surabaya (1829), Padang (1864), Makassar (1864), Cirebon (1866), Solo (1867), dan Pasuruan (1867).
Tahun 1951, enam tahun setelah proklamasi kemerdekaan, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia.
Maka, pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi DJB. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJB oleh pemerintah Indonesia, dengan besaran mencapai 97 persen.
Pada 1 Juli 1953, terbitlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia (BI), yang menggantikan DJB Wet.
Sejak saat itulah Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Regulasi tersebut merupakan ketentuan pertama yang mengatur BI sebagai bank sentral.
Tugas BI tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit.
Pada masa ini, terdapat Dewan Moneter (DM) yang bertugas menetapkan kebijakan moneter. DM diketuai Menteri Keuangan dengan anggota Gubernur BI dan Menteri Perdagangan.
Selanjutnya, BI bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh DM. Era berlalu, kini keberadaan BI mendapatkan mandat baru di bidang makroprudensial.
Perubahan besar ini secara otomatis membutuhkan penguatan internal melalui langkah transformasi BI.
Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), BI bertekad berperan aktif dalam pengembangan dan penguatan sektor keuangan di dalam negeri.
Salah satu Gubernur BI ialah Joseph Soedradjad Djiwandono, pemimpin BI kurun Maret 1993-Februari 1998.
Ia memiliki anak, yakni Thomas Djiwandono dan Budi Djiwandono—nama pertama terpilih menjadi Deputi Gubernur BI—dari hasil pernikahannya dengan anak dari Sumitro Djojohadikusumo.
Sumitro merupakan ayah dari Presiden Indonesia saat ini, Prabowo Subianto. Artinya, Thomas menduduki kursi Deputi Gubernur BI ketika pamannya menjadi orang nomor satu di Indonesia.
27 Januari 2026, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, dalam uji kelayakan dan kepatutan kandidat Deputi Gubernur, menjadi seorang “buta yang berjalan tanpa ragu”.
Sebab fakta Thomas merupakan keponakan Prabowo tidak bisa ditampik, namun Misbakhun mengakui si kandidat tetap profesional ketika bertugas nanti.
Bahwa fakta Pak Thomas keponakan (Prabowo), iya. Tapi dia tadi sangat profesional menjelaskan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan itu diambil dalam sebuah proses. Sehingga kalau menurut saya, isu itu bisa dikesampingkan bahwa ada profesionalisme,”
aku Misbakhun.
Ketika ditanya perihal ketiadaan pengalaman Thomas dalam ranah kebijakan moneter, Misbakhun mengatakan bahwa:
Pengalaman monetary policy itu bisa diperkuat ketika Thomas mempunyai pengalaman fiscal policy. Jadi saling melengkapi dan bisa berjalan dalam proses selanjutnya.”
Pertaruhan Rupiah di Meja Makan Keluarga
Manajer Riset Strategis CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet berkata, rekam jejak Thomas yang kental dengan afiliasi politik—sebagai Bendahara Umum Gerindra—dan hubungan kekerabatan dengan kekuasaan memunculkan persepsi negatif terkait potensi intervensi pemerintah terhadap kebijakan moneter.
Publik tidak bisa menafikan, meskipun disampaikan beliau sudah mundur dari partai, tapi rekam jejak historis menunjukkan beliau orang dekat dengan kepemimpinan saat ini yang menimbulkan risiko atau persepsi tidak begitu baik terutama dari aspek independensi Bank Sentral,”
kata Yusuf kepada owrite.
Karena dengan masuknya Thomas, ada kekhawatiran keputusan-keputusan BI “bisa” dipengaruhi oleh pandangannya dan akan bias terhadap kutub tertentu, misalnya pemerintah.
Sorotan utama tertuju pada risiko fiscal dominance, sebuah kondisi di kebijakan moneter (BI) disetir dan dipaksa tunduk untuk melayani kebutuhan fiskal (pemerintah/APBN).
Analogi ekonomi yang sehat ialah seperti sebuah kendaraan. Pemerintah yang agresif membelanjakan anggaran (untuk program seperti Makan Bergizi Gratis) berfungsi sebagai kaki yang menginjak ‘gas’ untuk pertumbuhan.
Sementara, BI berfungsi sebagai kaki yang menginjak ‘rem’ untuk menjaga stabilitas dan inflasi. Bahaya muncul ketika kedua ‘kaki’ dikendalikan oleh satu kepentingan yang sama.
(Kekhawatirannya) ketika ada intervensi dan bank sentral itu kehilangan kekuatan untuk mengatakan ‘tidak’ pada beberapa aspek yang nanti diminta oleh pemerintah dari sisi kolaborasi fiskal dan moneter,”
lanjut dia.
Jika intervensi terjadi dan BI gagal mengerem, inflasi bisa melonjak drastis. Ketika inflasi meningkat di luar target karena intervensi politik, maka harga barang naik. Dalam konteks daya beli masyarakat yang masih tertekan saat ini, kondisi tersebut adalah kabar buruk.
Pasar keuangan adalah indikator paling jujur dan cepat dalam merespons risiko ini. Pelemahan nilai tukar rupiah sesaat setelah nama Thomas mencuat sebagai kandidat kuat menjadi bukti nyata kegelisahan investor.
Market sudah me-highlight, salah satunya risiko tergerusnya independensi bank sentral dengan terpilihnya beliau. Ini dibuktikan dengan nilai tukar rupiah yang kembali melemah,”
Jelas Yusuf.
Selain itu, ada pula dampak jangka panjang terhadap Surat Berharga Negara (SBN). Jika persepsi independensi BI rusak, investor akan menuntut kompensasi risiko yang lebih tinggi.
Skenario moderatnya, investor tetap membeli SBN, tapi mereka meminta imbal hasil (yield) yang lebih tinggi lantaran risiko membesar. Imbal hasil tinggi bakal membebani bunga utang pemerintah di masa depan. Padahal, proporsi bunga utang negara meningkat dalam 10 tahun terakhir.
Ini adalah konsekuensi-konsekuensi yang dapat muncul ketika pemerintah tidak bisa, atau dalam hal ini Bank Sentral, tidak bisa memastikan independensinya,”
ucap dia.
Kompetensi dan Meritokrasi
Selain isu independensi, Yusuf juga menyoroti aspek kompetensi dan meritokrasi. Ia menilai, pengalaman Thomas di sektor moneter sangat minim jika dibandingkan dengan kandidat lain yang berasal dari karier internal BI dan juga menjadi kandidat Deputi Gubernur, Dicky Kartikoyono dan Solikin M Juhro.
Posisi Thomas yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam waktu singkat pun belum cukup membuktikan kapasitas teknokratisnya untuk jabatan strategis Deputi Gubernur BI.
Penempatan figur politik atau keluarga di posisi teknokratis tanpa basis meritokrasi yang kuat berpotensi merusak tata kelola lembaga negara, yang menurut Yusuf sebagai sinyal kemunduran bagi reformasi institusional pasca-1998.
Saya kira memang ada tren ke sana (kemunduran demokrasi). Semoga yang publik perkirakan ini salah, tapi memang ada tendensi ke sana. Orang-orang dekat dengan pemerintah ditempatkan tanpa menjalankan prinsip meritokrasi. Seandainya orang yang ditempatkan itu tidak punya pengalaman, tidak heran menimbulkan pertanyaan ‘apakah dia bisa menjalankan pekerjaannya?”
kata Yusuf.
Kini, publik dan pasar hanya bisa menunggu dan mengawasi. Apakah Thomas mampu membuktikan dirinya sebagai teknokrat yang independent, atau justru membenarkan ketakutan pasar bahwa BI menjadi “kasir” bagi ambisi politik pemerintah.