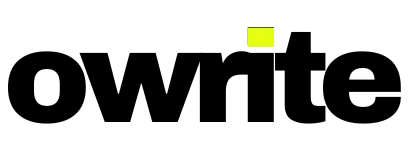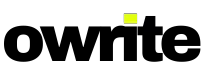Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah provinsi di Pulau Sumatera kembali dilanda bencana besar. Hujan ekstrem yang terus mengguyur diperkirakan sebagai pemicu utama, namun para pakar mengingatkan bahwa kerusakan ekosistem hulu dan tata kelola lahan yang buruk turut memperparah bencana.
Menurut sejumlah laporan dari media internasional dan nasional, termasuk hasil telaah lapangan dari para aktivis lingkungan, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dampak dari banjir dan longsor ini pun sangat luas, tidak hanya soal korban jiwa, melainkan juga krisis kemanusiaan, kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi besar.
Diketahui, hujan lebat mengguyur wilayah Sumatera sejak akhir November 2025, terutama di provinsi-provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
Intensitas curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat menyebabkan sungai–sungai meluap dan lereng-lereng bukit mengalami longsor, memporak-porandakan banyak kawasan perumahan dan desa.
Desa-desa di tepian sungai dan di lereng bukit terendam atau tertimbun material longsor, memaksa ribuan warga mengungsi mendadak. Banyak keluarga terpaksa meninggalkan rumah tanpa sempat membawa barang berharga.
Jaringan jalan dan jembatan rusak parah, membuat akses ke sejumlah wilayah terputus. Hal ini menyulitkan upaya evakuasi maupun distribusi bantuan, dan terpaksa dilakukan lewat jalur udara.
Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025, korban jiwa meninggal dunia mencapai 753 jiwa, dan 650 orang masih dinyatakan hilang.
Angka korban jiwa ini pun masih terus diperbarui seiring tim SAR dan sukarelawan membersihkan reruntuhan dan menyisir daerah terdampak. Artinya, kemungkinan korban jiwa bisa bertambah.
Dampak ekonomi juga besar, ribuan rumah rusak atau hilang, pertanian dan kebun penduduk terdampak banjir atau tertimbun, serta jalan dan jembatan yang putus. Akibatnya, pendapatan warga dan penghidupan sehari-hari ikut terganggu.
Selain itu, ribuan keluarga kini hidup dalam kondisi darurat, tinggal di tempat pengungsian sementara, dengan akses terbatas terhadap air bersih, makanan, dan layanan kesehatan.
Menurut Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian imbas banjir dan tanah longsor ini mencapai Rp68,67 triliun. Perhitungan kerugian ekonomi bencana banjir tersebut berdasarkan lima jenis kerugian.
Pertama, kerugian rumah yang masing-masing diperkirakan mencapai Rp30 juta per rumah. Kedua, kerugian jembatan dengan masing-masing biaya pembangunan kembali jembatan mencapai Rp1 miliar.
Ketiga, kerugian pendapatan keluarga sesuai dengan pendapatan rata-rata harian masing-masing provinsi dikali dengan 20 hari kerja. Keempat, kerugian lahan sawah dengan kerugian mencapai Rp6.500 per kg dengan asumsi per Ha dapat menghasilkan 7 ton. Kelima, perbaikan jalan per 1000 meter mencapai Rp100 juta.
Analisis dari sejumlah pakar lingkungan mengungkap bahwa bencana ini bukan sekadar akibat cuaca ekstrem. Faktor manusia, terutama kerusakan lingkungan, memainkan peran besar dalam memperparah dampak.
Banyak hulu kawasan aliran sungai (DAS) telah kehilangan tutupan hutan, akibat deforestasi, penebangan liar, dan konversi lahan untuk perkebunan atau pemukiman. Hutan yang seharusnya menyerap air hujan kini hilang, sehingga air langsung mengalir ke hilir dengan volume besar.
Tanpa penahan alami dari hutan, daya serap tanah menurun drastis, dan menjadikan daerah aliran sungai dan perbukitan sangat rentan terhadap longsor saat hujan lebat.
Dengan kondisi seperti ini, hujan ekstrem, bahkan hanya dalam hitungan hari, sudah cukup untuk memicu banjir bandang dan longsor besar.
Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS Universitas Gadjah Mada (UGM) Hatma Suryatmojo, menyatakan bencana banjir bandang di wilayah Sumatera sejatinya bukan peristiwa yang berdiri sendiri.
Bahkan, para ahli menilai fenomena ini merupakan bagian dari pola berulang bencana hidrometeorologi yang kian meningkat dalam dua dekade terakhir akibat kombinasi faktor alam dan ulah manusia.
Curah hujan memang sangat tinggi kala itu, BMKG mencatat beberapa wilayah di Sumut diguyur lebih dari 300 mm hujan per hari pada puncak kejadian. Curah hujan ekstrem ini dipicu oleh dinamika atmosfer luar biasa, termasuk adanya Siklon Tropis Senyar yang terbentuk di Selat Malaka pada akhir November 2025. Namun, cuaca ekstrem hanyalah pemicu awal. Dampak merusak banjir bandang tersebut sesungguhnya diperparah oleh rapuhnya benteng alam di kawasan hulu,”
Hatma melalui pernyataan tertulis yang diterima Owrite.
Berbagai hasil penelitian di hutan tropis alami di Kalimantan dan Sumatera menunjukkan kemampuan hutan untuk menahan dan menampung air hujan di tajuk (intersepsi) mencapai 15-35 persen dari hujan.
Sementara itu dengan permukaan tanah yang tidak terganggu, mampu memasukkan air ke dalam tanah (infiltrasi) hingga 55 persen dari hujan, sehingga limpasan permukaan (surface runoff) yang mengalir ke badan sungai hanya tersisa 10-20 persen saja.
Belum lagi kemampuan hutan untuk mengembalikan air ke atmosfer melalui proses evapotranspirasi yang bisa mencapai 25-40 persen dari total hujan.
Hatma pun turut menyayangkan terjadinya deforestasi masif yang telah berlangsung di banyak kawasan hulu Sumatra. Di Aceh misalnya, hingga 2020 sekitar 59 persen wilayah provinsi ini atau ±3,37 juta hektare masih berupa hutan alam.
Namun, data kompilasi BPS Aceh dan lembaga lingkungan menunjukkan provinsi ini kehilangan lebih dari 700.000 hektare hutan dalam kurun 1990–2020.
Artinya, meski tutupan hutan Aceh relatif masih luas, laju kehilangan hutannya signifikan sehingga meningkatkan kerentanan terhadap banjir.
Kondisi lebih memprihatinkan tampak di Sumatra Utara. Tutupan hutan Sumut tinggal sekitar 29 persen luas daratan atau ±2,1 juta hektare pada tahun 2020.
Hutan tersisa pun tersebar terfragmentasi di pegunungan Bukit Barisan bagian barat (termasuk sebagian Taman Nasional Gunung Leuser) dan enclave konservasi seperti di wilayah Tapanuli.
Salah satu benteng terakhir hutan Sumut adalah ekosistem Batang Toru di Tapanuli. Wilayah hutan tropis lebat inipun, kini terdesak oleh aktivitas manusia.
Ekosistem Batang Toru terus terdegradasi akibat maraknya konsesi dan aktivitas perusahaan, mulai dari penebangan liar, pembukaan kebun, hingga pertambangan emas. Hutan yang terfragmentasi dan tertekan ini kehilangan sebagian besar fungsi ekologisnya sebagai pengendali hujan dan penahan banjir,”
Hatma.
Sementara itu, Sumatra Barat memiliki proporsi hutan sekitar 54 persen dari luas wilayah atau ±2,3 juta hektare pada tahun 2020. Secara persentase masih lebih baik daripada Sumut, namun laju deforestasi Sumbar termasuk yang tertinggi.
Walhi Sumbar mencatat dalam periode 2001–2024 provinsi ini kehilangan sekitar 320 ribu hektare hutan primer dan total 740 ribu hektare tutupan pohon (hutan primer + sekunder). Bahkan, pada tahun 2024 saja deforestasi di Sumbar mencapai 32 ribu hektare. Sisa hutan Sumbar pun banyak berada di lereng curam Bukit Barisan sehingga ketika berkurang, risiko tanah longsor dan banjir bandang meningkat.
Tragedi banjir bandang yang melanda Sumatra pada November 2025 sejatinya merupakan akumulasi ‘dosa ekologis’ di hulu DAS. Cuaca ekstrem saat itu hanya pemicu, daya rusak yang terjadi tak lepas dari parahnya kerusakan lingkungan di wilayah hulu hingga hilir DAS,”
Hatma.
Selain itu, Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara, Rianda Purba, menyebut bahwa ekosistem Batang Toru saat ini adalah hutan penyangga hidrologis yang terus terkikis.
Ekosistem Harangan Tapanuli/Batang Toru merupakan salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di Sumatera Utara.
Secara administratif, 66,7 persen berada di Tapanuli Utara, 22,6 persen di Tapanuli Selatan, dan 10,7 persen di Tapanuli Tengah.
Sebagai bagian dari Bukit Barisan, hutan ini menjadi sumber air utama, mencegah banjir dan erosi, serta menjadi pusat Daerah Aliran Sungai (DAS) menuju wilayah hilir,”
Rianda Purba, Selasa, 2 Desember 2025.
Walhi pun mengindikasikan tujuh perusahaan sebagai pemicu kerusakan karena aktivitas eksploitatif yang membuka tutupan hutan Batang Toru.
Berikut rinciannya:
PT Agincourt Resources
Berdasarkan catatan Walhi, sepanjang 2015–2024, perusahaan ini telah mengurangi tutupan hutan dan lahan sekitar 300 hektare di DAS Batang Toru.
Lokasi TMF (Tailing Management Facility) berada sangat dekat Sungai Aek Pahu yang mengaliri Desa Sumuran. Warga disekitaran lokasi menyampaikan bahwa sejak beroperasinya PIT Ramba Joring, air sungai sering kali keruh saat musim hujan.
Berdasarkan AMDAL, PT Agincourt Resources memproduksi enam juta ton emas per tahun, dan berencana meningkatkan kapasitas menjadi 7 juta ton dengan membuka 583 hektare lahan baru untuk fasilitas tailing, termasuk penebangan 185.884 pohon.
Investigasi Walhi menemukan bahwa sekitar 120 hektare sudah dibuka. Dokumen dampak lingkungan perusahaan itu sendiri mencantumkan risiko, seperti perubahan pola aliran sungai, peningkatan limpasan, penurunan kualitas air, hilangnya vegetasi, rusaknya habitat satwa.
PLTA Batang Toru (PT NSHE)
Proyek PLTA telah menyebabkan hilangnya lebih dari 350 hektare tutupan hutan di sepanjang 13 km daerah sungai, serta gangguan fluktuasi debit sungai, sedimentasi tinggi akibat pembuangan limbah galian terowongan dan pembangunan bendungan, potensi polusi sungai bila limbah galian mengandung unsur beracun.
Video luapan Sungai Batang Toru di Jembatan Trikora juga menunjukkan gelondongan kayu dalam jumlah besar. Walhi Sumut mensinyalir kayu-kayu tersebut berasal dari area pembangunan infrastruktur PLTA.
PT Toba Pulp Lestari (PKR)
Hutan Tanaman Industri TPL telah lama dikritik atas konversi hutan alam menjadi perkebunan kayu.
Total luas konsesi PT TPL saat ini adalah 167.912 hektare di Sumut, berdasarkan revisi izin terakhir pada tahun 2020.
Dalam rilisnya, PT TPL hanya mengakui 186 hektare unit Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) yang ada di kawasan Ekosistem Batang Toru. Luasan itu saja sudah setara 251 ukuran lapangan sepak bola.
Selain menimbulkan bencana ekologis, perusahaan ini juga kerap melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat adat, dan membuang limbah sembarang.
Walhi Sumut dengan organisasi masyarakat sipil lain di Tano Batak, yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup TPL, berulang kali menuntut penutupan perusahaan ini.
Ragam desakan dan gugatan kami layangkan sejak tahun 90-an kala perusahaan masih bernama PT Inti Indorayon Utama (IIU). Namun, sudah 3 dekade perjuangan kami, negara masih juga abai,”
Walhi melalui akun Instagram resminya, Selasa 2 Desember 2025.
PT Pahae Julu Micro-Hydro Power – PLTMH Pahae Julu
Menurut Walhi, PLTMH Pahae Julu mendapatkan suntikan dana dari China. Pembangunan PLTMH ini juga turut mengganggu fungsi hidrolis aliran sungai Batang Toru.
Meski skala proyek lebih kecil, pembukaan vegetasi di kawasan Pahae Julu tetap memberi dampak signifikan. Daerah ini merupakan wilayah lereng dengan risiko longsor tinggi.
Pembukaan lahan untuk akses dan fasilitas mikro-hidro membuat tanah mudah tererosi, terutama pada musim hujan. Efeknya pun semakin terasa ketika curah hujan ekstrem turun secara bersamaan di kawasan hulu.
PT SOL Geothermal Indonesia – Perusahaan Energi
Panas Bumi Eksplorasi di Tapanuli Utara dianggap ikut menambah tekanan ekologis, dengan menghasilkan kapasitas 330 Mega Watt (MW).
Pembangunan jalan, pengeboran, dan pembukaan area eksplorasi menghilangkan vegetasi yang seharusnya berfungsi menstabilkan tanah.
Ketika hujan ekstrem hadir, daerah yang sudah terganggu struktur tanahnya menjadi salah satu titik longsor.
PT Sago Nauli Plantation
PT Sago Nauli adalah perusahaan sawit yang selama ini melakukan ekspansi di daerah penyangga Ekosistem Batang Toru. Perkebunan sawit di kawasan ini menjadi penyebab hilangnya tutupan hutan dan menurunnya fungsi hidrologis di wilayah tangkapan air.
Menurut Walhi, perusahaan tidak pernah mengungkap data terbuka mengenai berapa luas hutan yang dikonversi di dalam lanskap Batang Toru. Di lapangan, masyarakat melaporkan konflik agraria, perampasan lahan, dan dugaan ketidaksesuaian HGU yang hingga kini belum terselesaikan.
Kami menemukan fakta, PT Sago Nauli sudah mulai melakukan ekspansi ke kawasan ekosistem Batang Toru, utamanya di Sibio-bio, Kecamatan Sibabangung, Tapanuli Tengah, dengan prakira luasan sekitar 200 hektare. Daerah Sibabangunng menjadi salah satu area terdampak parah dalam tragedi banjir bandang Tapanuli.”
Walhi.
PTPN III Batang Toru Estate
Sebagai perusahaan negara, PTPN III tidak bisa menutup mata atas kontribusinya terhadap alih fungsi hutan di Batang Toru.
Mengacu pada laporan Walhi terhadap peliputan investigatif Mongabay, mencatat bahwa PTPN III mengelola HGU seluas ±1.917 hektare yang masuk ke wilayah Batang Toru, luasan yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari penyusutan kawasan penyangga hutan.
Keberadaan perkebunan skala besar ini tidak hanya mengubah bentang alam, tetapi juga menekan ruang hidup masyarakat sekitar yang bergantung pada lahan pertanian.
Walhi menilai PTPN III ikut berperan dalam fragmentasi habitat dan penurunan ketahanan ekologis di daerah tersebut.
Di tengah krisis ekologis, negara seharusnya menjadi garda terdepan pemulihan, bukan bagian dari masalah,”
Walhi.
Walhi Sumatera Utara menegaskan bahwa hadirnya perkebunan monokultur, termasuk ekspansi PKR di sekitar Ekosistem Batang Toru, adalah bentuk kejahatan lingkungan dan eksploitasi rakus terhadap alam.
Kawasan Batang Toru adalah ekosistem esensial yang seharusnya menjadi benteng terakhir keselamatan ekologis Sumatera Utara, namun justru dirusak oleh konversi hutan menjadi tegakan industri yang menghilangkan daya serap air, menghancurkan habitat satwa kunci, dan meruntuhkan keseimbangan ekologis.
Rangkaian bencana ekologis yang terjadi baru-baru ini, seperti banjir bandang, longsor, hingga rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) di berbagai kabupaten/kota, bukanlah musibah alam semata, tetapi konsekuensi langsung dari perampasan ruang hidup oleh industri monokultur yang merobek jantung Batang Toru.
Walhi Sumut menuntut penghentian total aktivitas monokultur di kawasan esensial ini, serta pemulihan ekologis yang berpihak pada keselamatan rakyat, bukan pada kepentingan korporasi,”
Walhi.
Lembaga pemantau hutan Forest Watch Indonesia (FWI) mengatakan bahwa deforestasi hutan di Indonesia pada 2017-2021 dengan nilai rata-rata 2,54 juta hektare per tahun atau setara dengan 6 kali luas lapangan sepakbola per menit, telah menggiring Indonesia pada jurang krisis iklim.
Situasi ini memperlihatkan bahwa hutan Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tingginya tingkat kerusakan sumber daya hutan terjadi hampir di setiap region. Region Kalimantan masih menunjukan nilai rata-rata deforestasi sebesar 1,11 juta hektare per tahun, diikuti Papua 556 ribu hektare per tahun, Sumatera 428 ribu hektare per tahun, Sulawesi 290 ribu hektare per tahun, Maluku 89 ribu hektare per tahun, Bali Nusa 38 ribu hektare per tahun, dan Jawa 22 ribu hektare per tahun.
Kerusakan hutan-hutan di Indonesia yang rupanya sangat masif ini terkuak dengan makin canggihnya teknologi penginderaan jauh yang mampu menghitung kerusakan hutan lebih detail.
Hilangnya tutupan hutan selalu diikuti dengan hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur iklim mikro, sumber pangan papan masyarakat adat-masyarakat lokal, konservasi air dan tanah, areal bernilai konservasi tinggi, biodiversitas, potensi obat-obatan, sumber pangan dan gizi dari hutan, energi, serta nilai sejarah kebudayaan, bahkan sebagai sumber pengetahuan yang belum tercatat,”
FWI dalam laporannya.
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan sekitar 98 persen berupa pulau-pulau kecil, yang dikelola dengan menggunakan pendekatan kegiatan ekstraktif sumber daya alam.
Dari total luas pulau-pulau kecil Indonesia, ada sekitar 874 ribu hektare atau 13 persen dari total luas daratan pulau-pulau kecil yang telah dibebani izin industri ekstraktif SDA, seperti penebangan hutan sekitar 310 ribu hektare ,tambang sekitar 245 ribu hektare, hutan tanaman sekitar 94 ribu hektare, perkebunan sekitar 194 ribu hektare dan tumpang tindih sekitar 30 ribu hektare.
Aktivitas industri ekstraktif di pulau kecil terbukti telah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat yang tinggal. FWI mencatat, antara tahun 2017-2021 nilai rata-rata laju deforestasi di pulau-pulau kecil mencapai 79 ribu hektare pertahun, atau setara 3 persen dari nilai laju deforestasi nasional.
Hadirnya industri ekstraktif di pulau-pulau kecil ditengarai oleh kebijakan-kebijakan yang mendukungnya serta lemahnya perlindungan terhadap ekosistem yang khas seperti pulau kecil,”
FWI.
Sementara itu, jika mengacu pada data Kementerian Kehutanan pada tahun 2024, berdasarkan hasil pemantauan tahunan mengenai kondisi hutan dan angka deforestasi di Indonesia, yang mencakup 187 juta hektare, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, menunjukkan bahwa luas lahan berhutan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 95,5 juta hektare, atau 51,1 persen dari total daratan. Dari angka tersebut, sekitar 91,9 persen (87,8 juta hektare) berada di dalam kawasan hutan.
Sementara itu, angka deforestasi netto tahun 2024 tercatat sebesar 175,4 ribu hektar. Angka ini diperoleh dari deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektare dikurangi hasil reforestasi yang mencapai 40,8 ribu hektare. Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan sekunder dengan luas 200,6 ribu hektare (92,8 persen), di mana 69,3 persen terjadi di dalam kawasan hutan dan sisanya di luar kawasan hutan.
Untuk menekan angka deforestasi, Kementerian Kehutanan mengklaim telah melaksanakan upaya reforestasi melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 217,9 ribu hektar pada tahun 2024. Angka tersebut merupakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di dalam kawasan seluas 71,3 ribu hektar dan di luar kawasan seluas 146,6 ribu hektar, baik yang berasal dari sumber pendanaan APBN maupun pendanaan non APBN.