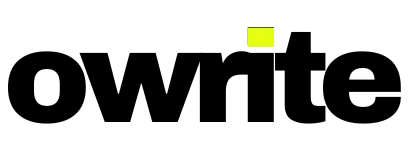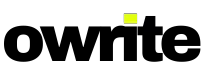Bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dalam beberapa waktu terakhir, tidak bisa dilihat semata-mata sebagai peristiwa alam.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, mengatakan tragedi tersebut merupakan akumulasi dari persoalan tata kelola perizinan yang telah berlangsung secara masif selama puluhan tahun, khususnya di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.
Sehingga yang terjadi adanya alih fungsi lahan. Ketika bencana itu muncul, sesungguhnya akibat yang ditimbulkan dari perizinan-perizinan yang selama ini memang tumpang tindih dan tidak jelas kewenangannya,”
ujar Trubus kepada owrite baru-baru ini.
Ditambahkannya, masalah utama bukan hanya pada jumlah izin, tetapi pada sistem perizinan yang sejak awal tidak tertata dengan baik. Banyak izin diterbitkan tanpa koordinasi antarlembaga, bahkan saling bertabrakan satu sama lain.
Ia menceritakan, sejak era Reformasi kewenangan perizinan pada awalnya diberikan kepada pemerintah daerah. Namun seiring waktu, sebagian kewenangan itu ditarik kembali ke pemerintah pusat.
Masalahnya, daerah tidak mau melepas sepenuhnya. Karena perizinan itu terkait langsung dengan sistem politik lokal, terutama saat pilkada.
Mereka didukung pemilik modal, kemudian dijanjikan terkait dengan pengelolaan, seperti sumber daya mineral, hutan, perkebunan, ada yang muncul sistem “hijau”, artinya belum jadi tapi sudah ditawarkan,”
jelasnya.
Di sisi lain, sambung Trubus, pemerintah pusat juga memiliki kepentingan besar. Ketika perizinan sepenuhnya diserahkan ke daerah, muncul kekhawatiran daerah menjadi terlalu proteksionis dan menutup informasi, bahkan melahirkan “raja-raja kecil” di wilayahnya.
Menurut Trubus, sistem perizinan yang ideal adalah sistem kewenangan bertingkat dan kolaboratif antara pusat dan daerah.
Kalau nilai investasinya triliunan, itu kewenangan pusat. Kalau di bawah itu, (kewenangan) daerah. Tapi masalahnya, aturan teknisnya tidak pernah benar-benar jelas,”
jelasnya.
Ditegaskan Trubus, undang-undang sering kali menyebutkan bahwa perizinan adalah kewenangan daerah. Namun dalam praktiknya, pemerintah pusat tetap turun tangan. Ketidakjelasan inilah yang memicu konflik kewenangan dan membuka ruang penyimpangan.
Dijelaskannya, perizinan tidak berhenti hanya pada penerbitan izin. Substansi utama dari sebuah izin adalah pengawasan dan penegakan hukum. Namun di Indonesia, implementasi dua hal ini masih sangat lemah.
Idealnya, kata Trubus, perizinan dilakukan secara kolaboratif. Pemerintah daerah harus dilibatkan, karena merekalah yang memiliki wilayah, sumber daya manusia, dan menanggung langsung dampak lingkungan.
Bahkan, sering kali daerah mensyaratkan agar tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal agar ada manfaat ekonomi langsung. Namun dalam praktiknya, kolaborasi ini sering gagal.
Pusat tidak sepenuhnya percaya pada daerah karena banyak kasus penyimpangan. Sebaliknya, daerah merasa pusat terlalu dominan dan tidak adil dalam pembagian hasil,”
bebernya.
Trubus juga menyinggung bahwa konflik antara pemerintah pusat dan daerah dalam perizinan pernah sampai pada titik ekstrem. Ada kepala daerah yang secara terbuka menyatakan ketidakpuasan terhadap sistem bagi hasil, bahkan mengancam ingin “lebih dekat” ke negara lain.
Kasus-kasus seperti itu akhirnya banyak berujung pada penegakan hukum. Banyak kepala daerah ditangkap KPK, karena kongkalikong dengan pengusaha, bahkan melibatkan pihak luar negeri,”
tandasnya.