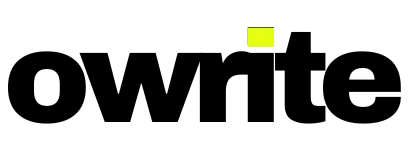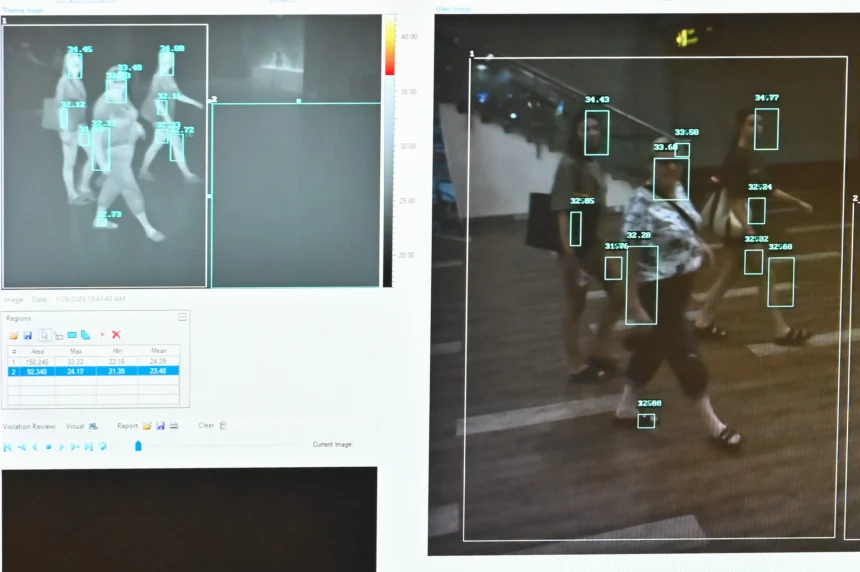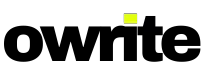Pengamat Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita, menyatakan, penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap praktik patronase serta keterlibatan Politically Exposed Person (PEPs) dalam pelaksanaan program MBG, tidak bisa dibaca sekadar sebagai masalah administratif, melainkan peringatan awal adanya risiko pembajakan kebijakan oleh kepentingan kekuasaan.
Bacaan saya, temuan ICW ini bukan sekadar isu administratif, melainkan sinyal dini tentang masalah desain kebijakan,”
kata Ronny kepada owrite.
Dirinya menegaskan, besarnya proporsi mitra yang memiliki afiliasi politik menunjukkan mekanisme seleksi yang tidak netral.
Ketika hampir sepertiga mitra program sosial nasional terafiliasi dengan partai politik, aparat, militer, atau keluarga elite, artinya mekanisme seleksi mitra tidak steril dari kekuasaan,”
ujarnya.
Dalam kerangka kebijakan publik modern, Ronny menyebut kondisi ini sebagai state capture risk, yakni ketika program negara berpotensi ditarik ke orbit kepentingan politik, bukan kepentingan publik.
Menurut dia, situasi tersebut telah memenuhi unsur konflik kepentingan secara substantif, meskipun belum tentu langsung menjadi pelanggaran pidana.
Ia pun menjelaskan, konflik kepentingan akan menjadi pelanggaran hukum apabila afiliasi politik terbukti memengaruhi proses seleksi mitra, alokasi anggaran, pengawasan, atau menimbulkan kerugian negara.
Risiko terbesarnya adalah program berubah dari kebijakan sosial menjadi instrumen patronase politik. Negara membayar, elite menikmati, sementara kualitas layanan ke publik menjadi nomor dua,”
paparnya.
Ronny juga menyoroti fakta, bahwa program MBG telah berjalan hampir 10 bulan tanpa aturan teknis dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Dalam perspektif good governance, kondisi ini ia nilai sangat serius.
Menjalankan program nasional tanpa aturan teknis ibarat membangun gedung tanpa gambar dan desain, mungkin berdiri, tapi rawan roboh dan sulit dimintai pertanggungjawaban,”
ucapnya.
Standar Ketat dan SOP Tegas
Menurut hemat Ronny, ketiadaan SOP justru menciptakan ruang diskresi berlebihan, yang disebut discretion overload, yaitu terlalu banyak ruang tafsir dan terlalu sedikit kontrol.
Dampaknya, risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran menjadi sangat tinggi, mulai dari mark-up biaya pangan, penurunan kualitas makanan demi margin, hingga munculnya yayasan fiktif atau semi-aktif.
Ia menegaskan, lemahnya standar keamanan pangan bukan persoalan administratif semata.
Bahayanya langsung, bukan sekadar isu administratif. Kita bicara soal anak-anak dan kelompok rentan,”
ujar Ronny.
Tanpa standar yang ketat, menurutnya risiko keracunan massal, gizi buruk terselubung, hingga krisis kepercayaan publik sangat mungkin terjadi.
Peneliti senior itu pun menilai pihak yang paling dirugikan adalah penerima manfaat, terutama anak-anak dari keluarga miskin. Karena itu, ia mendesak langkah korektif segera dilakukan.
Pertama, moratorium terbatas untuk audit tata kelola dan mitra. Kedua, terbitkan aturan teknis dan SOP nasional yang mengikat. Ketiga, buka data mitra, anggaran, dan kinerja ke publik,”
katanya.
Ia pun memberikan peringatan keras:
Pendeknya, program sosial tidak boleh dikelola seperti proyek politik. Kalau itu terjadi, yang kenyang bukan rakyat, tapi jejaring kekuasaan.”
Desain Tata Kelola Program Lemah
Sementara itu, peneliti Center for Economic and Law Studies (CELIOS) Galau D. Muhammad, menilai temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait afiliasi politik yayasan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai gejala serius pembajakan kebijakan dalam spektrum belanja sosial negara.
Menurut Galau, keberadaan puluhan yayasan yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan bukan anomali administratif, melainkan simptom struktural dari lemahnya desain tata kelola program.
Kalau kita baca dari temuan ICW, itu ada puluhan yayasan yang memiliki afiliasi politik dalam program MBG. Ini menjadi simptom yang sebenarnya bisa dilihat di banyak wilayah, bahwa adanya policy capture dalam spektrum belanja sosial,”
ujar Galau pada owrite.
Secara ekonomi, sambungnya, MBG merupakan program dengan insentif besar yang ditujukan secara spesifik kepada kelompok rentan.
Namun ketika pelaksana program memiliki afiliasi politik, orientasi kebijakan berisiko bergeser.
Ketika ada mitra pelaksana yang memiliki afiliasi politik, praktik di lapangan yang seharusnya objektif dan teknokratik menjadi terdistorsi,”
ujarnya.
Menurut Galau, pelibatan yayasan dalam program MBG semestinya berbasis pada kapabilitas, sertifikasi dan kemampuan mengelola rantai pasok pangan.
Ironisnya, ketiadaan mekanisme seleksi dan audit yang ketat justru membuka ruang bagi penunjukan yayasan minim pengalaman.
Tidak wajar ada yayasan baru, minim pengalaman dalam manajemen pangan, dipaksakan mengelola distribusi dan rantai pasok. Ini sangat berisiko,”
tegasnya.
Galau menilai, konflik kepentingan muncul ketika aktor yang memiliki pengaruh politik sekaligus menerima manfaat ekonomi dari implementasi kebijakan.
Konflik kepentingan ini menjadi pelanggaran etik, ketika ada relasi langsung terhadap proses kebijakan dan aktor yang sama mendapatkan manfaat dalam implementasinya,”
jelasnya.
Dalam kondisi tersebut, sistem tata kelola yang longgar dinilai gagal memitigasi penyalahgunaan. Ia juga menyoroti fakta, bahwa MBG berjalan tanpa aturan teknis dan standar operasional yang memadai.
Ketika pemerintah gagal memastikan mekanisme itu diatur dalam satu kerangka hukum yang jelas, negara kehilangan fiscal control framework,”
paparnya.
Dampaknya, standar biaya, mutu gizi, hingga sanksi atas pelanggaran tidak memiliki pijakan yang kuat. Risiko paling nyata menyasar langsung penerima manfaat.
Lemahnya standar keamanan pangan dampaknya sangat serius. Kita kehilangan baseline dan arah, sementara negara hanya memastikan distribusi tanpa mengukur outcomes,”
ujarnya.
Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan pemborosan fiskal jangka panjang dan kegagalan investasi gizi. Galau menekankan, pihak yang paling dirugikan adalah anak-anak dan keluarga dengan kerentanan pangan tinggi, terutama di wilayah terpencil. Karena itu, ia mendorong langkah korektif drastis.
Pemerintah perlu melakukan moratorium total program MBG untuk audit transparan dan komprehensif, memastikan efisiensi ekonomi dan dampak nyata investasi negara,”
ungkapnya.
Menurutnya, program sosial tidak cukup diperlakukan sebagai proyek penyerapan anggaran.
Negara harus menjadi penjamin standar, bukan sekadar penyalur anggaran. Pembayaran harus dikaitkan dengan kinerja dan mutu, serta transparan agar publik bisa mengawasi langsung,”
katanya.
Ia pun menutup dengan menegaskan, bahwa MBG hanya akan menjadi investasi bermakna jika terbebas dari relasi kuasa dan afiliasi politik.
Yang sedang kita bangun adalah masa depan anak-anak yang tidak punya pilihan selain percaya pada negara,”
pungkasnya.
Jadi Alat Konsolidasi Politik
Dari hasil penelitian tersebut, ICW menyimpulkan bahwa pelaksanaan MBG sarat akan praktik politik patronase dan konflik kepentingan.
Hal ini tercermin dari hubungan individu di yayasan penyelenggara dengan partai politik, tim pemenangan, pendukung Prabowo maupun Joko Widodo, militer, dan aparat penegak hukum.
Keterkaitan ini mengindikasikan adanya dugaan distribusi sumber daya atau akses tertentu kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan politik.
Selain itu, pola ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas dukungan politik, lantaran penerima akses dan manfaat cenderung membalas budi dengan memberikan loyalitas dan dukungan kepada pihak pemberi kemudahan.
Sehingga, program ini diduga digunakan sebagai alat konsolidasi politik ketimbang memberi manfaat bagi publik.
Hal tersebut juga diperkuat dengan temuan penelusuran yang menunjukkan, bahwa yayasan-yayasan pengelola SPPG tidak memiliki relevansi, kompetensi, dan kualifikasi dalam memberikan makanan kepada penerima manfaat MBG.
Contohnya, sejumlah yayasan justru terafiliasi dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan POLRI, serta militer.
Sedangkan tugas pokok dan fungsi dari institusi tersebut secara jelas tidak berkaitan dengan giat pengolahan pangan, serta peningkatan kesehatan dan gizi.
Adanya afiliasi yayasan penyedia MBG yang mengarah ke institu tersebut justru menunjukan bahwa upaya untuk memperkuat jejaring patronase di berbagai lini termasuk pada sektor penegakan hukum dan militer patut diduga sedang terjadi.
Afiliasi tersebut juga menunjukan bahwa tidak ada standar yang jelas untuk memilih dan menentukan yayasan sebagai mitra BGN.
Ketiadaan standar kompetensi ini juga tercermin dari munculnya afiliasi bisnis pada individu dalam yayasan, yang justru bergerak di bidang non pangan ataupun kesehatan. Seperti bisnis properti, telekomunikasi, konstruksi, hingga pertambangan.
Nihil Integritas
Di sisi lain, temuan bahwa sejumlah yayasan terafiliasi dengan orang-orang yang pernah terlibat dalam kasus korupsi mengindikasikan bahwa program ini tidak mempertimbangkan prinsip integritas dan antikorupsi.
Hal ini sekaligus memperkuat dugaan, bahwa pemilihan mitra lebih dipengaruhi oleh kedekatan politik dan afiliasi daripada rekam jejak etik.
Tanpa mempertimbangkan hal tersebut, maka potensi penyelewengan semakin terbuka lebar. Terlebih, anggaran negara yang dikelola berjumlah besar. Setiap SPPG disebutkan bisa mengelola anggaran sekitar Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan.
Dengan batas maksimal SPPG yang dapat dikelola berjumlah 10 unit per yayasan, artinya setiap yayasan berpotensi mengelola hingga Rp10 miliar per bulan.
Bila yayasan penyedia SPPG justru diisi oleh orang yang pernah terlibat kasus korupsi, jaminan bahwa anggaran MBG dikelola secara tepat guna akan semakin sulit dicapai.
Temuan juga menunjukkan masalah tata kelola MBG dengan adanya dugaan keterlibatan yayasan yang terafiliasi dengan BGN.
Tenaga ahli di tim teknis BGN yang ikut menjadi penyedia MBG, menunjukan bahwa upaya mekanisme pengawasan program dan pengendalian konflik kepentingan tidak pernah menjadi perhatian.
Apalagi, dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional, tugas BGN disebutkan berkaitan dengan fungsi pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.
Pengawasan BGN terhadap pelaksanaan program berisiko sulit diwujudkan ketika terdapat individu dalam BGN yang ikut menjadi eksekutor program.
Individu dalam BGN tersebut menghadapi konflik kepentingan, lantaran independensi dan efektivitas pengawasan berpotensi terpengaruh.
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, program MBG sangat berisiko disalahgunakan untuk kepentingan politik dan memperkuat jaringan patronase.
Oleh karena itu, rekomendasi tegas yang diajukan adalah menghentikan program MBG dan mengalokasikan anggarannya untuk kebijakan lain yang lebih bermanfaat bagi publik.