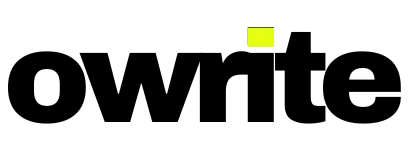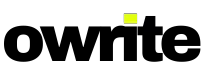Mata Koin
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers turut mengeluarkan sikap tegas menanggapi wacana pembentukan RUU ini.
Alih-alih menyehatkan ruang publik, regulasi tersebut berpotensi besar menciptakan “narasi tunggal” versi negara dan memperparah praktik kriminalisasi terhadap jurnalis dan warga sipil.
Ada bahaya laten dalam draf regulasi ini: hegemoni kebenaran oleh penguasa dan tumpang tindih aturan yang berujung pada penjara (overkriminalisasi).
Direktur Eksekutif LBH Pers Mustafa Layong, memperingatkan bahwa RUU ini dirancang dengan logika yang menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya wasit kebenaran.
Dalam ekosistem demokrasi, kebenaran seharusnya diuji melalui diskursus publik dan mekanisme pers yang bebas, bukan distempel oleh badan negara.
Naskah Akademik yang seharusnya memuat data dan fakta lapangan secara akademis tidak mampu menunjukkan urgensi dibalik narasi pembentukan produk regulasi ini.
Orientasi rancangan pembentukan perundang-undangan baru ini lagi-lagi menyasar pada pemidanaan masyarakat sipil, khususnya kelompok masyarakat sipil dengan narasi “antek asing” yang berulang kali didengungkan oleh presiden dalam pidato-pidato kenegaraan,”
ujar Mustafa.
Muatan sanksi pidana pada sebuah produk regulasi baru, yang tidak dapat dibuktikan urgensi penyusunannya, bakal menimbulkan overkriminalisasi baru.
Kondisi ini tak hanya menambah beban finansial negara, tapi juga mengancam demokrasi dan mempersempit ruang kebebasan sipil.
Regulasi ini, lanjut Mustafa, dianggap tak menanggulangi disinformasi, tapi berpotensi memidana pengkritik pemerintah.
Padahal pemerintah sudah dibekali cukup banyak peraturan (UU ITE dan KUHP) yang juga rawan disalahgunakan demi menghambat penyebaran kritik atau narasi berbeda dengan pemerintah.
Berdasar Naskah Akademik, RUU ini mengamanatkan pembentukan lembaga otoritas sebagai pengawas independen yang berwenang memantau ekosistem informasi digital.
Pembentukan lembaga serupa pun dimandatkan dalam naskah RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.
Pembentukan lembaga pengawasan serupa mengingatkan kembali Indonesia pada masa Orde Baru yang berperan sebagai alat utama kontrol media dan propaganda pemerintah dalam membatasi kebebasan pers dan menyensor informasi kritis terhadap rezim saat itu,”
jelas Mustafa.
Ia memperingatkan, bahwa pembentukan kelembagaan baru jangan digunakan sebagai panggung “bagi-bagi kue” dengan menyediakan jalur hijau bagi aparat negara yang tidak seharusnya memegang fungsi dan jabatan pada ruang sipil.
Konsensus Pemahaman
Pemerhati Budaya dan Komunikasi Digital Firman Kurniawan Sujono, mengingatkan pemerintah untuk tidak menggunakan pendekatan “narasi tunggal” dalam penyusunan RUU ini.
Keterlibatan publik dan definisi yang rigid menjadi kunci agar regulasi ini tidak berubah menjadi alat represi.
Ancaman disinformasi global saat ini sangat nyata dan berbahaya, namun ia menekankan bahwa “imunitas” (literasi) masyarakat jauh lebih efektif daripada sekadar sensor atau pemblokiran. Firman tidak menampik urgensi perlindungan negara di era digital.
Ia mencontohkan kasus di Prancis dan Myanmar—disinformasi yang diproduksi secara canggih (termasuk menggunakan Artificial Intelligence/AI)—mampu mengguncang stabilitas nasional dan memicu konflik horizontal.
Disinformasi itu memang sebuah ancaman yang nyata. Tujuan (RUU) untuk membangun ketahanan informasi nasional. Jadi, undang-undang ini penting di tengah situasi global dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Permainan sekarang itu bukan perang fisik, tetapi sebuah negara bisa dilemahkan dengan disinformasi,”
jelas Firman kepada owrite.
Dalam konteks ini, negara memang wajib hadir untuk membangun ketahanan informasi nasional. Firman berpendapat ada dua cara membangun ketahanan informasi: pencegahan melalui edukasi (imunitas) atau penindakan melalui pemblokiran (filtering).
Indonesia sebagai negara demokrasi lebih diutamakan undang-undang ini ke arah pencegahan, ketahanan informasi. Ketika itu yang diutamakan akan bermanfaat buat masyarakat tanpa muncul kecurigaan pembatasan informasi, pengekangan kebebasan berpendapat, dan sebagainya,”
kata dia.
Firman menegaskan, bila ada keperluan untuk memblokir disinformasi dan propaganda asing dalam kategori mendesak (emergency), wajib dilakukan dengan sangat berlapis yakni melibatkan akademisi dan para ahli.
Artinya bukan hanya merepresentasikan kepentingan pemerintah semata, namun mekanisme tersebut tidak boleh dilakukan sepihak oleh pemerintah.
Menanggapi kekhawatiran bahwa RUU ini bakal mengisolasi Indonesia seperti Great Firewall di China—sistem kombinasi teknologi dan kebijakan legislatif yang digunakan pemerintah Tiongkok untuk menyaring, memantau, dan memblokir konten internet asing, menciptakan ruang siber domestik yang terisolasi—Firman mengingatkan bahaya memukul rata semua “konten asing” sebagai ancaman.
Indonesia membutuhkan pertukaran data dan riset global untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Ia juga menyoroti bahwa algoritma filtering bisa memiliki bias tergantung siapa pengaturnya.
Bila tidak hati-hati dan cermat, sistem bisa saja memblokir kritik yang sah hanya karena dianggap bertentangan dengan kepentingan rezim. Kalau undang-undang ini dibentuk, tidak semua hal asing harus dan harus diblokir.
Ketika terbukti (propaganda), negara punya lembaga intelijen dan punya pengalaman pengaruh ideologi dari luar dan sebagainya. Itu ada algoritmanya. Hal yang semacam itu perlu digunakan sebagai pertimbangan dan tidak membabi buta segala hal dari asing harus ditangkal,”
ucap Firman.
Perihal kritik masyarakat sipil soal potensi “pasal karet” dan tumpang tindih dengan regulasi serupa, Firman memberikan solusi konkret: perjelas definisi dan spesifikasikan ranah yang diatur, terutama untuk hal-hal baru yang belum terdapat dalam hukum saat, umpama kejahatan Deepfake AI. Maka pendefinisian harus tegas: apa yang disebut dengan konten asing, adu domba, hasutan, misalnya.
Itu perlu dijelaskan dengan rigid dan melibatkan banyak pihak untuk memberikan pendapat. Jadi, pendekatan bukan satu arah. Perlu mengetengahkan dialog antarpihak bahwa Indonesia menghadapi situasi perkembangan global, kemajuan teknologi, dan sebagainya,”
kata dia.
Keberhasilan RUU ini sangat bergantung pada kepercayaan publik. Bila pemerintah memaksakan kehendak tanpa dialog, regulasi ini justru bakal melahirkan resistensi. Kalau narasi tunggal dari rezim, alhasil publik emoh percaya.
Maka kata kuncinya adalah ‘melibatkan banyak pihak’,”
tutur Firman.